Bulan ini, kita kembali memasuki sebuah penanda waktu yang unik dan kaya makna di Indonesia, khususnya di Jawa. Bagi sebagian besar umat Muslim, kita menyebutnya Muharam, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Momen ini adalah awal tahun baru Islam, penuh dengan anjuran ibadah seperti puasa Asyura dan refleksi mendalam atas perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW.
Namun, di tanah Jawa, dan mungkin juga akrab bagi warga Semarang, bulan yang sama ini lebih dikenal dengan sebutan Suro. Suro bukan sekadar penamaan kalender Jawa yang merupakan perpaduan Islam dengan penanggalan Hindu-Buddha. Lebih dari itu, Suro lekat dengan nuansa sakral, kehati-hatian, dan tradisi-tradisi kuno yang masih lestari hingga kini.
Secara syariat Islam, Muharam adalah bulan yang penuh berkah. Peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah menjadi inti penanda tahun baru ini. Hijrah bukan hanya perpindahan fisik, tapi juga simbol perpindahan dari keburukan menuju kebaikan, dari kegelapan menuju cahaya, dari kondisi yang tak kondusif menuju masyarakat yang lebih baik.
Maka, Muharam adalah momen krusial untuk introspeksi. Sudahkah kita berhijrah ke arah yang lebih baik? Apakah ibadah kita semakin khusyuk, akhlak kita semakin mulia, dan kontribusi kita untuk sesama semakin nyata? Puasa sunah di Hari Asyura (10 Muharam) juga mengingatkan kita pada keselamatan Nabi Musa AS dari Firaun, sebuah simbol pembebasan dari kezaliman dan menuju kebenaran. Esensinya jelas: peningkatan spiritual dan kualitas diri.
Di sisi lain, Suro membawa nuansa yang berbeda. Bulan ini dianggap “wingit” atau keramat, penuh dengan energi spiritual yang kuat dalam pandangan Kejawen dan tradisi Jawa. Banyak masyarakat yang masih melestarikan tradisi seperti jamasan pusaka (membersihkan benda-benda pusaka), tirakatan (berdoa atau bermeditasi semalam suntuk di tempat-tempat keramat), atau bahkan menunda hajatan besar seperti pernikahan.
Filosofi di balik tradisi Suro cenderung pada pencarian ketenteraman batin, harmoni dengan alam semesta, dan penghormatan mendalam terhadap leluhur. Ada keyakinan bahwa pada bulan ini, batas antara alam nyata dan alam gaib menjadi lebih tipis, sehingga diperlukan sikap hati-hati, hening, dan perenungan mendalam.
Fenomena Muharam dan Suro ini adalah bukti nyata kekayaan budaya dan spiritualitas bangsa Indonesia. Keduanya, meskipun dengan penekanan dan ritual yang berbeda, sejatinya memiliki benang merah yang sama: momen untuk introspeksi, membersihkan diri, dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.
Bagi umat Muslim, Muharam adalah kesempatan untuk menguatkan iman dan mengamalkan ajaran agama secara lebih baik. Bagi mereka yang kental dengan tradisi Jawa, Suro adalah waktu untuk menghormati warisan leluhur, mencari ketenangan batin, dan menjaga keseimbangan hidup.
Di era yang serba cepat ini, penting bagi kita untuk memahami kedua perspektif ini dengan lapang dada. Bukan untuk saling mempertentangkan, apalagi merendahkan, melainkan untuk saling memperkaya khazanah spiritual dan budaya kita. Muharam mengingatkan kita akan perjalanan agung Nabi dan dorongan untuk berhijrah, sementara Suro mengajak kita untuk menepi sejenak, merenung, dan menata ulang batin.
Mari kita jadikan bulan Muharam/Suro ini sebagai kesempatan emas untuk membersihkan diri, baik secara lahir maupun batin. Semoga tahun baru ini membawa kita semua pada kebaikan, keberkahan, dan langkah-langkah yang lebih positif dalam hidup.



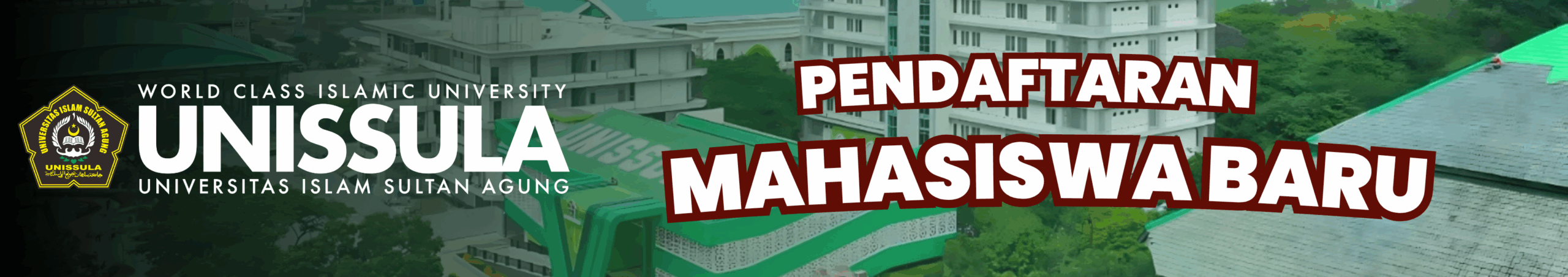

Leave a Reply